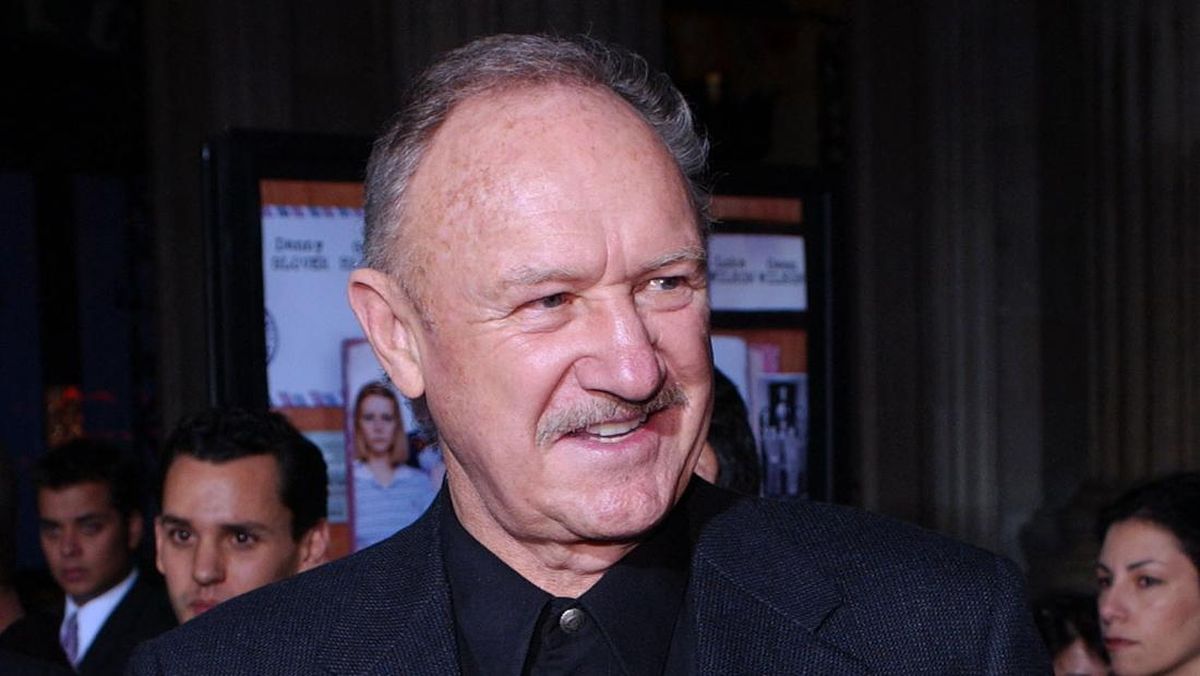Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi
CNNIndonesia.comJakarta, CNN Indonesia --
Dalam sejarah ekonomi global, terdapat momen-momen krusial ketika sistem yang tampak kokoh dan mapan tiba-tiba mengalami pergeseran arah akibat tindakan sepihak.
Hari-hari ini kita menyaksikan peristiwa tersebut. Amerika Serikat di bawah Donald Trump memilih jadi episentrum disrupsi dengan kebijakan tarifnya.
Kebijakan yang diambil pada awal April 2025 ini bukan hanya instrumen fiskal semata, melainkan ekspresi dari perubahan fundamental dalam cara AS memandang peran mereka di dalam sistem perdagangan dunia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Trump memberlakukan tarif yang mencapai 145 persen terhadap produk asal China dan menerapkan tarif universal 10% -- sebelumnya ia menunda kebijakan tarif resiprokal selama 90 hari. Trump sesungguhnya sedang mengajukan tesis politik: bahwa dunia harus tunduk pada logika hubungan koersif, sementara kepercayaan terhadap tatanan multilateral yang dibentuk pasca-Perang Dunia II telah kehilangan relevansinya.
Retorika yang menyertai kebijakan ini mempertegas arah pandang tersebut. Trump menyampaikan dengan penuh keangkuhan bahwa "seluruh dunia menelepon Washington," karena dunia membutuhkan pasar dan konsumen AS.
Pernyataan tersebut tidak hanya menunjukkan kepercayaan diri berlebih terhadap daya tarik ekonomi domestik AS, tetapi juga menandakan pengabaian simbolis terhadap prinsip perdagangan global yang inklusif.
Di mata banyak negara, tindakan tersebut bukan isyarat kekuatan, melainkan alarm bahwa negara adidaya itu tak lagi bersedia menganut kepemimpinan sistem global yang berbasiskan aturan bersama.
Di sinilah letak paradoksnya: negara yang dulu membentuk dan memimpin sistem perdagangan bebas kini menjadi aktor revisionis dalam sistem ciptaannya sendiri.
Kebijakan tarif Trump seolah mempertegas bahwa kekuatan hegemoni AS tidak lagi bersifat inklusif. Dalam istilah Gramscian, kita menyaksikan degradasi dari hegemoni menjadi dominasi.
Hegemoni mensyaratkan konsensus, artikulasi nilai bersama, dan legitimasi internasional. Ketika instrumen koersif seperti tarif digunakan secara sepihak dan tanpa konsolidasi institusional, maka ia bukan lagi bentuk kekuasaan hegemoni, tetapi gejala disfungsi struktural dari kekuasaan global yang kehilangan daya pikatnya.
Dunia pun merespons dengan cara yang berbeda dari masa lalu. Negara yang sebelumnya bersedia menyesuaikan diri dengan tekanan ekonomi Amerika, kini menunjukkan kecenderungan untuk merintis jalur perdagangan alternatif, menghidupkan kembali mekanisme regional, dan mempercepat lahirnya dunia multipolar dalam bidang ekonomi.
Misalnya, negara-negara Asia Tenggara menggelar pertemuan darurat, Uni Eropa mengaktifkan kembali agenda-agenda kerja sama dagang yang tertunda dengan Amerika Latin, Timur Tengah, dan Australia.
China, sebagai pihak utama yang ditarget oleh kebijakan tarif Trump, menunjukkan respons yang tidak sekadar reaktif dengan Tarif 125%, melainkan strategis.
Di bawah tekanan eksternal, Beijing memperlihatkan kalkulasi strategis yang kontras dengan ketegangan di Washington. Bahkan, Xi Jinping menegaskan negaranya tidak takut dengan penindasan yang tak masuk akal dari Trump.
China memperluas jaringan ekonomi internasionalnya ke wilayah Global South, dari Asia Tenggara hingga Afrika dan Amerika Latin. Sebelumnya, di dalam negeri, Beijing menyusun kebijakan fiskal ekspansif yang bertujuan untuk memperkuat konsumsi domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap ekspor, sekaligus menjaga kestabilan ekonomi pasca-krisis properti.
Akhir 2024 lalu, Pemerintahan Xi Jinping menggelontorkan dana talangan sebesar 1,4 triliun dolar untuk meredam tekanan utang pemerintah lokal, dan menjadikan belanja publik sebagai motor pemulihan.
Dari sisi luar negeri, diplomasi dagang China semakin menonjolkan fleksibilitas. Semua ini menandai kebangkitan diplomasi ekonomi yang tidak hanya bersifat utilitarian, melainkan terencana secara geopolitik.
China menunjukkan keunggulan sistemik. Negara tersebut kini memproduksi lebih dari dua pertiga kendaraan listrik dunia, mendominasi baterai, panel surya, dan bahkan teknologi nuklir generasi keempat.
China juga memimpin dalam jumlah paten dan publikasi ilmiah, serta memiliki angkatan laut terbesar di dunia yang dibangun dari kekuatan industri domestiknya.
Sementara di sisi lain, Amerika semakin kesulitan mempertahankan kapasitas produksinya, sekutu-sekutunya justru mulai dirangkul China untuk membentuk koalisi baru berbasis interdependensi.
China kini menampilkan dirinya bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai alternatif.
Ketika Trump memutuskan hubungan dengan sekutu lama dan merusak struktur perdagangan global, Xi Jinping mencoba menawarkan kestabilan, pembiayaan, dan akses ke pasar yang sangat-sangat besar.
Ironisnya, retorika anti-China dari Washington justru memperkuat posisi Beijing di banyak negara berkembang. Investasi China di sejumlah negara berkembang melonjak. Hubungan dagang dengan Meksiko dan Brasil berkembang pesat sebagai jalur ekspor tak langsung ke pasar AS. Bukan karena mereka berideologi pro-China, tetapi karena keterdesakan pragmatisme ekonomi.
Diplomasi ekonomi China hari ini telah bergeser menjadi gerakan proaktif yang merangkul dunia yang kecewa dan merasa ditindas oleh inkonsistensi kebijakan AS.
Di Eropa, guncangan akibat tarif Trump mempercepat lahirnya inisiatif strategis untuk membebaskan diri dari dominasi ekonomi AS. Uni Eropa, yang sebelumnya terpecah dalam berbagai kepentingan nasional terkait isu perdagangan, kini mulai menyadari bahwa ketergantungan terhadap pasar AS merupakan risiko sistemik.
Ursula von der Leyen bergerak cepat untuk menyelesaikan negosiasi dengan Mercosur, meninjau ulang kebuntuan perjanjian dengan Australia, serta mempercepat dialog dengan negara-negara Timur Tengah, Uni Emirat Arab, dan juga China.
Namun perlawanan terhadap proteksionisme bukanlah proses yang mulus. Di tengah gelombang multilateral baru ini, muncul juga ketegangan internal akibat kekhawatiran domestik. Ketegangan ini menunjukkan bahwa dunia pasca-hegemoni tidak hanya ditandai oleh perpecahan antarnegara, tetapi juga oleh konflik antara kebutuhan untuk integrasi global dan desakan politik lokal yang menuntut proteksi.
Sementara dunia mulai menata ulang arsitektur perdagangan, Amerika justru mempertaruhkan posisinya sebagai jangkar stabilitas ekonomi global.
Dalam sistem Bretton Woods, AS adalah penyedia likuiditas utama, pengusung nilai tukar stabil, dan penjamin keterbukaan pasar. Kini, ketika kebijakan fiskal dan moneter digunakan untuk menghukum lawan dan menekan sekutu, reputasi dolar AS sebagai safe currency pun tergerus.
Seperti yang dilaporkan Financial Times, para ekonom memperingatkan kebijakan tarif Trump memicu ketidakpercayaan terhadap dolar AS, yang selama ini menjadi jangkar stabilitas global.
Kenaikan yield obligasi AS bersamaan penurunan nilai dolar, menandakan potensi pelarian modal-sebuah sinyal bahwa status "istimewa" dolar sebagai mata uang cadangan dunia terancam.
Inilah ironi besar dari unilateralisme ekonomi Trump. Di satu sisi, menegaskan kedaulatan nasional, tapi di sisi lain berpotensi memperlemah posisi Amerika dalam rantai nilai global.
Memimpin negara dengan defisit perdagangan besar, ketergantungan tinggi pada impor komponen strategis, serta utang publik yang menumpuk, Trump memilih untuk memberlakukan tarif tanpa kesiapan substitusi domestik. Dan ketika tarif menyebabkan kenaikan harga bahan baku dan barang konsumsi, industri dalam negeri AS menderita, inflasi naik, dan investasi asing menurun karena ketidakpastian kebijakan.
Jika situasi ini berlarut-larut, AS justru menciptakan stagflasi yang mereka coba hindari sejak dekade 1970-an.
Namun yang lebih mengkhawatirkan bukanlah dampak ekonomi jangka pendek, melainkan fragmentasi geopolitik jangka panjang.
Dunia kini menghadapi dua kemungkinan ekstrem: di satu sisi, terbentuknya dua blok perdagangan global yang saling berseberangan, yakni blok Amerika Serikat dan blok China. Di sisi lain, kita menyaksikan lahirnya tatanan perdagangan yang semakin cair dan asimetris, negara-negara bergerak lincah memanfaatkan satu kekuatan global untuk mengimbangi yang lain.
Dalam lanskap baru ini, kekuasaan tak lagi ditentukan oleh siapa yang paling besar, melainkan oleh siapa yang paling gesit secara diplomatik dan paling piawai merajut aliansi.
Pilihan yang diambil AS dalam beberapa tahun ke depan menentukan posisi strategisnya dalam tatanan baru ini.
Jika Amerika tetap bersikukuh pada jalur unilateral, meminggirkan sekutu, dan menjadikan ekonomi sebagai alat koersif semata, maka ia akan menyaksikan degradasi hegemoninya. Bukan karena dikalahkan dalam perang terbuka, tetapi ditinggalkan oleh dunia yang telah beralih ke cara kerja yang lebih plural dan adaptif.
Trump mungkin menilai perang dagang kali ini 'mudah' dimenangkan. Namun sejarah menunjukkan bahwa perdagangan bukanlah arena pertarungan, melainkan ruang untuk menyusun koalisi, membentuk tatanan, dan memperkuat legitimasi.
Ketika negara-negara lain membangun jembatan, Amerika tidak seharusnya membangun tembok. Sebab kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk memaksa dunia tunduk, melainkan kebijaksanaan untuk membuat dunia ikut serta.
(vws/vws)

 1 day ago
3
1 day ago
3